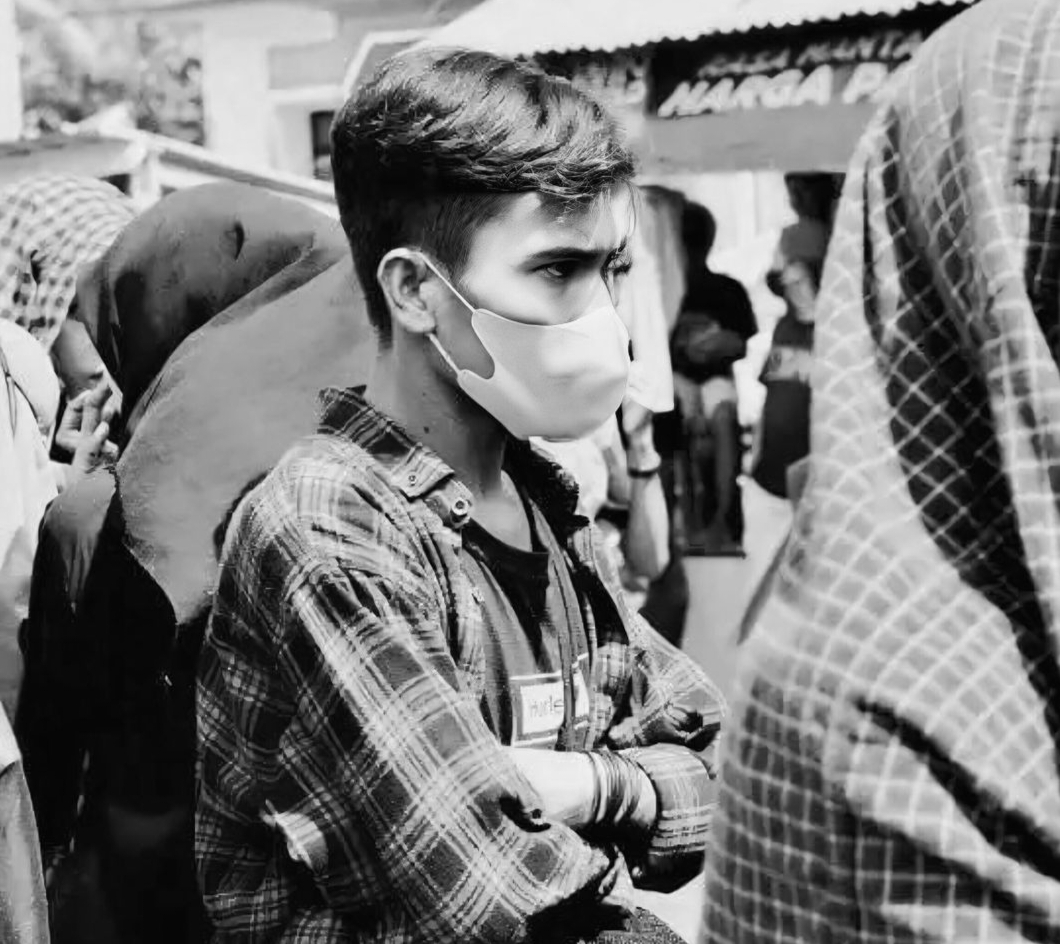Ditulis Oleh: Abdul Muarif Korois
(Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Indonesia)
Beberapa malam yang lalu, jagat media sosial kembali dikejutkan oleh beredarnya video seorang driver ojek online (ojol) yang dilindas kendaraan taktis (rantis). Bukan sekadar terlindas, tetapi benar-benar dilindas, tubuhnya remuk di bawah ban baja, nyawanya ditindih oleh besi kekuasaan. Bagi banyak orang, video itu bukan hanya rekaman peristiwa tragis, melainkan juga cermin betapa rapuh martabat manusia di negeri yang katanya berdiri di atas asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang lebih menyakitkan adalah respons negara yang datang begitu cepat tetapi hampa: sebuah permintaan maaf. Kalimat singkat yang seolah-olah cukup untuk menghapus darah rakyat, seakan-akan nyawa manusia bisa diganti dengan kata-kata penyesalan. Pertanyaan pun muncul di benak banyak orang: apakah maaf cukup untuk menggantikan nyawa? Apakah maaf bisa mengembalikan rasa percaya rakyat pada aparat yang mestinya melindungi mereka?
Fenomena ini tidak bisa hanya dibaca sebagai insiden kecelakaan. Ia adalah cermin dari pola yang lebih luas, pola yang berulang dalam sejarah relasi negara dengan rakyatnya. Dalam catatan sejarah Indonesia, kita berulang kali menyaksikan bagaimana kekuasaan begitu gampang mengorbankan rakyat kecil, lalu mencoba menutup tragedi itu dengan kalimat permintaan maaf atau janji evaluasi yang tidak pernah sungguh ditepati. Dari Tragedi Trisakti tahun 1998, di mana mahasiswa ditembak aparat lalu hanya diredam dengan janji reformasi tanpa penyelesaian hukum yang jelas, hingga kasus-kasus kontemporer seperti kriminalisasi petani Kendeng yang mempertahankan tanahnya, pola yang sama selalu berulang; rakyat jatuh korban, negara meminta maaf, lalu semua kembali seperti semula. Luka tidak sembuh, keadilan tidak datang, dan rakyat semakin kehilangan kepercayaan.
Teori kritis, yang banyak dipengaruhi pemikiran Mazhab Frankfurt seperti Horkheimer, Adorno, dan Habermas, membantu kita membongkar lapisan makna dari peristiwa ini. Bagi teori kritis, bahasa bukan hanya sarana komunikasi, melainkan juga instrumen kuasa. Bahasa bisa membebaskan, tapi juga bisa menindas. Permintaan maaf yang keluar dari mulut aparat negara dalam peristiwa driver ojol yang dilindas rantis bukanlah bahasa yang membebaskan. Ia adalah bahasa kuasa, bahasa yang dipakai bukan untuk membuka ruang dialog, melainkan untuk meredam kritik dan mengalihkan fokus publik. Permintaan maaf dijadikan perisai simbolik agar rakyat berhenti menuntut pertanggungjawaban struktural. Inilah yang disebut Habermas sebagai distorsi komunikasi, ketika wacana tidak lagi berfungsi sebagai arena deliberasi yang sejajar, tetapi berubah menjadi instrumen hegemonik untuk mempertahankan dominasi.
Dalam perspektif manajemen konflik, situasi ini memperlihatkan bagaimana negara salah total dalam mengelola konflik. John Burton menekankan bahwa konflik sosial pada dasarnya tidak selalu buruk, ia bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperjuangkan kebutuhan dasar mereka. Namun, syaratnya konflik harus dikelola secara adil. Morton Deutsch juga mengingatkan bahwa penyelesaian konflik harus fokus pada kebutuhan nyata para pihak, bukan sekadar meredakan permukaan. Apa yang dilakukan negara melalui permintaan maaf hanyalah bentuk avoidance, penghindaran konflik. Negara tidak masuk ke inti persoalan: mengapa ada rantis di tengah rakyat? Mengapa prosedur pengamanan bisa sebegitu brutal? Siapa yang bertanggung jawab? Semua pertanyaan substantif itu disapu bersih dengan kalimat maaf. Itulah pseudo-conflict management, pengelolaan konflik semu yang hanya memoles luka dari luar tanpa menyentuh akar penyakitnya. Hasilnya justru memperparah ketidakpercayaan.
Jika kita tarik lebih jauh, peristiwa ini menyingkap watak asli relasi negara dengan rakyat kecil di Indonesia. Kata-kata Pramoedya Ananta Toer yang legendaris “Polisi lebih dekat dengan pejabat daripada petani” mendadak kembali hidup dalam memori kolektif. Polisi, yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, tampak lebih khawatir pada murka pejabat ketimbang pada jeritan rakyat. Driver ojol yang dilindas rantis itu bukan hanya korban individual, ia simbol. Ia simbol dari betapa murah harga nyawa rakyat kecil dibandingkan stabilitas politik. Ia simbol dari bagaimana negara rela mengerahkan kekuatan besi demi melindungi kursi pejabat, tetapi enggan mengulurkan tangan tulus pada rakyat yang berlumur darah.
Jika kita kaitkan dengan literatur komunikasi politik, fenomena permintaan maaf ini bisa dipahami melalui teori image repair yang dikemukakan oleh William Benoit. Dalam situasi krisis, elite politik biasanya menggunakan strategi retorika untuk memperbaiki citra mereka. Permintaan maaf adalah salah satu strategi yang paling sering dipakai. Namun, strategi ini hanya berhasil jika diikuti tindakan nyata yang konsisten. Tanpa itu, permintaan maaf justru berubah menjadi bumerang. Publik tidak hanya tidak percaya, tetapi juga merasa dilecehkan. Dalam kasus ojol yang dilindas rantis, publik tahu bahwa maaf itu tidak diikuti akuntabilitas hukum, tidak diikuti evaluasi struktural, tidak diikuti pemulihan yang layak bagi keluarga korban. Maka maaf itu tidak lagi terdengar sebagai ekspresi penyesalan, melainkan sebagai penghinaan simbolik.
Kita bisa mengingat contoh lain untuk mempertegas pola ini. Dalam tragedi Kanjuruhan 2022, di mana ratusan suporter sepak bola meninggal akibat gas air mata aparat, negara juga meminta maaf. Namun, apa yang terjadi kemudian? Hingga kini, pertanggungjawaban hukum masih kabur, banyak pihak hanya dihukum ringan, sementara luka keluarga korban tidak pernah sungguh diobati. Kasus demi kasus memperlihatkan konsistensi yang menyedihkan: ketika rakyat jatuh, negara hanya sanggup mengucapkan maaf, lalu segera bergerak menjaga citra, bukan menegakkan keadilan.
Dari perspektif sosiologis, hal ini menunjukkan lemahnya legitimasi negara. Max Weber pernah menekankan bahwa negara memiliki monopoli atas kekerasan yang sah. Namun, monopoli itu hanya bisa diterima masyarakat jika dijalankan dengan legitimasi. Ketika aparat menggunakan kekerasan secara brutal lalu menutupinya dengan maaf tanpa akuntabilitas, legitimasi itu terkikis. Rakyat akan melihat bahwa monopoli kekerasan tidak lagi sah, melainkan sekadar monopoli kekuasaan. Inilah titik berbahaya: ketika rakyat kehilangan kepercayaan, mereka bisa mencari jalannya sendiri di luar sistem, dan itu bisa berujung pada disintegrasi sosial.
Karena itu, langkah yang seharusnya dilakukan negara jelas. Pertama, akuntabilitas nyata. Aparat yang terlibat harus diadili secara terbuka sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa anggota Polri wajib bertindak profesional, proporsional, dan bertanggung jawab, serta tunduk pada mekanisme pengawasan internal dan eksternal. Kedua, pemulihan yang layak, karena kehilangan nyawa tidak bisa dibayar dengan sekadar ucapan, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hidup dan keamanan diri. Ketiga, reformasi struktural dalam penggunaan kekuatan aparat agar tragedi serupa tidak terulang, merujuk pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tugas Polri, yang menegaskan batasan penggunaan kekuatan agar tetap proporsional, sah, dan akuntabel. Tanpa itu, setiap permintaan maaf hanya akan menjadi kata-kata kosong.
Namun, harapan itu tampaknya masih jauh. Kita hidup di negeri di mana luka rakyat lebih sering diperlakukan sebagai ancaman stabilitas ketimbang sebagai alasan untuk berbenah. Kita hidup di negeri di mana maaf lebih murah daripada keadilan. Dan selama pola itu tidak diubah, selama aparat masih lebih dekat dengan pejabat ketimbang dengan rakyat, maka tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang.
Maka, marilah kita jangan biarkan peristiwa ini sekadar lewat sebagai tontonan di layar ponsel. Driver ojol yang dilindas rantis adalah pengingat keras bahwa besi kekuasaan bisa menimpa siapa saja. Jika hari ini kita diam, besok mungkin giliran kita yang dilindas, lalu hanya diberi maaf. Kita harus bersuara, kita harus menuntut, sebab hanya dengan itu kita menjaga martabat kemanusiaan kita. Luka ini tidak bisa ditutup dengan maaf. Luka ini hanya bisa disembuhkan dengan keadilan, dan keadilan hanya mungkin lahir jika negara sungguh-sungguh berpihak pada rakyat.
Selama maaf masih dipakai sebagai ganti nyawa, selama aparat masih menjadi pelindung kursi pejabat, dan selama darah rakyat kecil masih dianggap murah, selama itu pula kita akan terus hidup dalam lingkaran tragedi. Dan pada akhirnya, yang tersisa hanyalah ironi: negeri yang berdiri atas nama kemerdekaan justru menjelma penindas bagi rakyatnya sendiri. (***)