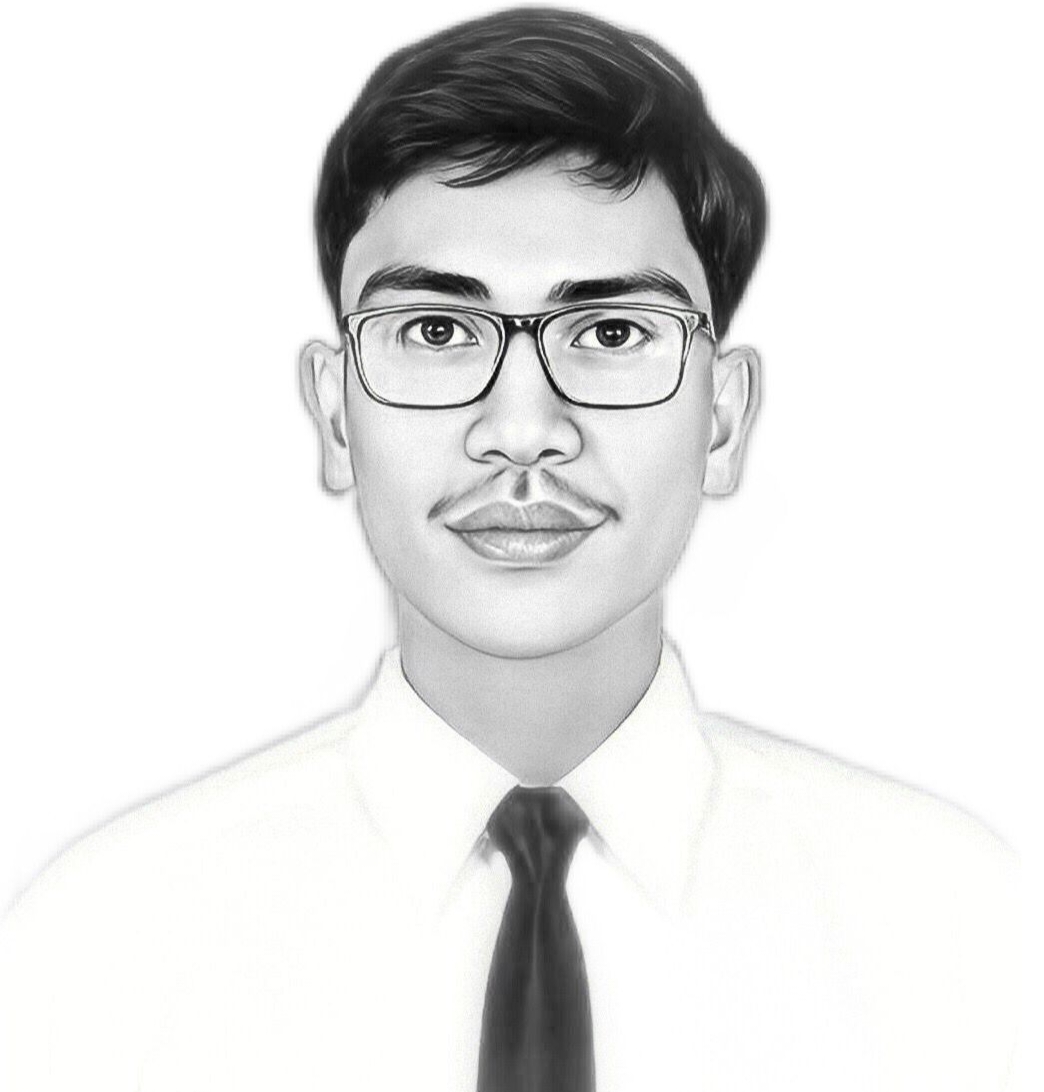Oleh: ABDUL MUARIF KOROIS, S.H
(Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Indonesia)
Di banyak pelosok Indonesia, ada satu figur yang keberadaannya tidak selalu mendapat sorotan, tetapi justru sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil: pengacara kampung. Ia bisa seorang sarjana hukum, bisa pula sekadar tokoh masyarakat yang paham seluk-beluk aturan, atau bahkan mantan aktivis yang akrab dengan mekanisme birokrasi. Namun yang pasti, mereka hadir untuk membantu warga menghadapi masalah hukum sehari-hari.
Fenomena ini bukan hal baru. Di sebuah desa di Maluku Utara, misalnya, saya pernah menemui seorang bapak paruh baya yang dikenal warga sebagai “ahlinya urusan tanah”. Setiap kali ada konflik batas kebun, warisan yang diperebutkan, atau persoalan sengketa kecil dengan perusahaan perkebunan, warga akan lebih dulu datang kepadanya ketimbang langsung ke kantor polisi atau pengadilan. “Kalau ke pengadilan, pasti butuh biaya besar,” kata seorang warga. “Kalau ke pak tua ini, paling kita hanya kasih rokok dan kopi, tapi masalah selesai”.
Cerita serupa bisa ditemui di Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Mereka yang disebut “pengacara kampung” menjadi rambu awal sebelum masyarakat benar-benar berhadapan dengan aparat hukum. Sebutan ini punya dua wajah. Dalam arti negatif, pengacara kampung sering dilekatkan pada “pengacara gadungan,” orang yang mengaku bisa mengurus perkara padahal tidak punya lisensi resmi. Tetapi dalam arti positif, ia justru sosok yang menyalurkan aspirasi rakyat kecil yang selama ini terpinggirkan dari akses hukum.
Fenomena pengacara kampung sejatinya lahir dari sebuah kenyataan pahit: hukum di Indonesia kerap lebih mudah diakses oleh mereka yang punya modal. Bagi rakyat kecil, proses hukum sering dipandang sebagai sesuatu yang mahal, rumit, dan melelahkan. Biaya jasa advokat, ongkos transportasi ke pengadilan, hingga “biaya tak resmi” yang konon sering dibicarakan di warung kopi semuanya membuat hukum terasa eksklusif (Kompas, 2021).
Secara teoretis, kondisi ini bukan hal aneh. Richard Quinney (1970), tokoh kriminologi kritis, sudah lama menyatakan bahwa hukum bukanlah perangkat netral, melainkan instrumen kelas berkuasa. Pierre Bourdieu bahkan lebih jauh: hukum baginya adalah modal simbolik yang hanya bisa dimainkan oleh mereka yang memiliki kapital, baik kapital ekonomi, politik, maupun sosial (Bourdieu, 1987).
Lalu bagaimana dengan rakyat kecil yang tidak punya itu semua? Mereka berhadapan dengan struktur hukum yang timpang. Di sinilah pengacara kampung mengambil peran: menjadi “jembatan” antara rakyat miskin dan dunia hukum yang serba mahal.
Kalau kita meminjam istilah Antonio Gramsci, pengacara kampung bisa disebut sebagai “intelektual organik” (Gramsci, 1971). Mereka bukan intelektual yang lahir dari menara gading, melainkan bagian dari masyarakat yang sama-sama berjuang di bawah. Tugas mereka bukan sekadar menjelaskan hukum, tetapi juga mendampingi, menafsirkan, bahkan memperjuangkan agar hukum tetap punya wajah manusia.
Dalam praktiknya, banyak pengacara kampung yang lebih berperan sebagai mediator sosial ketimbang pembela di pengadilan. Mereka mencari jalan damai, menengahi konflik, atau sekadar memberikan pemahaman bahwa hukum tidak harus selalu berakhir di meja hakim. Namun di balik kesederhanaan itu, ada satu pesan moral penting: bahwa hukum semestinya tidak hanya menjadi milik segelintir orang kaya, melainkan hak semua warga negara (Satjipto Rahardjo, 2006).
Semangat yang sama sesungguhnya bisa kita temukan dalam novel “The Street Lawyer” karya John Grisham. Tokoh utamanya, Michael Brock, adalah pengacara muda yang awalnya bekerja di firma hukum raksasa. Ia menikmati gaji besar, gedung tinggi, dan kehidupan mewah, sampai suatu peristiwa membuatnya tersadar bahwa di luar sana ada jutaan orang miskin yang tidak pernah mendapat akses keadilan. Michael lalu memilih meninggalkan kenyamanan itu demi membela kaum papa, para gelandangan, dan orang-orang tanpa rumah.
Membaca kisah Michael Brock, kita seolah bercermin. Hukum yang diidealkan sebagai pelindung semua orang ternyata sering berpihak hanya pada pemilik modal. Tanpa advokat, suara orang miskin nyaris tidak pernah terdengar di pengadilan.
Ada tiga pesan utama dari novel itu yang relevan bagi konteks Indonesia. Pertama, hukum berpihak pada yang kuat, siapa yang punya kuasa ekonomi dan politik, dialah yang lebih mudah memenangkan perkara. Kedua, akses keadilan adalah barang mewah, membayar pengacara hebat jelas tidak mungkin dilakukan oleh tukang ojek, buruh harian, atau nelayan tradisional. Dan ketiga, profesi hukum adalah pilihan moral, seorang pengacara selalu dihadapkan pada dilema: apakah bekerja untuk kapital, atau membela kemanusiaan (Grisham, 1998).
Apa yang dikisahkan Grisham lewat novel fiksi sesungguhnya nyata terjadi di Indonesia. Kita bisa melihatnya dalam kasus-kasus penggusuran warga miskin di kota besar. Tanpa advokat, warga hanya bisa pasrah menerima keputusan pemerintah atau perusahaan. Demikian juga dalam kasus sengketa tanah adat; sering kali masyarakat kalah karena tidak mampu menghadirkan pembela yang mumpuni. Di titik inilah, pengacara kampung mengambil peran penting. Mereka mungkin tidak sekelas advokat top dengan tarif ratusan juta, tetapi keberadaan mereka membuat rakyat kecil tidak sepenuhnya sendirian.
Saya teringat kisah seorang warga pesisir di Maluku Utara yang lahannya hendak diambil untuk proyek pembangunan. Ia datang ke pengacara kampung setempat, seorang sarjana hukum yang belum berstatus advokat resmi. Meski sederhana, pengacara kampung itu membantu menyiapkan surat-surat, menghubungkan dengan LSM, bahkan menemani warga ke kantor bupati. Akhirnya, meski tidak sepenuhnya menang, warga berhasil mendapat ganti rugi yang lebih layak. Itulah wajah nyata keadilan yang mungkin tidak akan masuk headline media, tetapi sangat dirasakan oleh mereka yang hidup di pinggir.
Dari cerita-cerita nyata di desa, teori para ilmuwan sosial, hingga inspirasi dari novel John Grisham, kita bisa menarik satu simpulan umum: hukum tidak akan pernah benar-benar adil jika hanya dilihat dari teks peraturan. Ia baru bermakna ketika hadir di tengah masyarakat, menjawab kebutuhan mereka, dan berpihak pada yang lemah. Pengacara kampung, dengan segala keterbatasannya, adalah bukti bahwa rakyat kecil punya cara sendiri untuk memperjuangkan keadilan. Mereka adalah “street lawyer” versi Indonesia.
Jika profesi hukum di negeri ini ingin benar-benar bermakna, para advokat profesional, akademisi hukum, hingga pemerintah harus belajar dari mereka. Sebab, justru dari tangan para pengacara kampunglah hukum tetap memiliki wajah manusia, sederhana, membumi, dan berpihak pada mereka yang kerap dilupakan.
Referensi :
• Bourdieu, Pierre. (1987). The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field. Hastings Law Journal.
• Gramsci, Antonio. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers.
• Grisham, John. (1998). The Street Lawyer. Doubleday.
• Kompas. (2021). “Akses Hukum Bagi Kaum Miskin Masih Terbatas
• Quinney, Richard. (1970). The Social Reality of Crime. Little, Brown and Company.
• Rahardjo, Satjipto. (2006). Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia.(***)